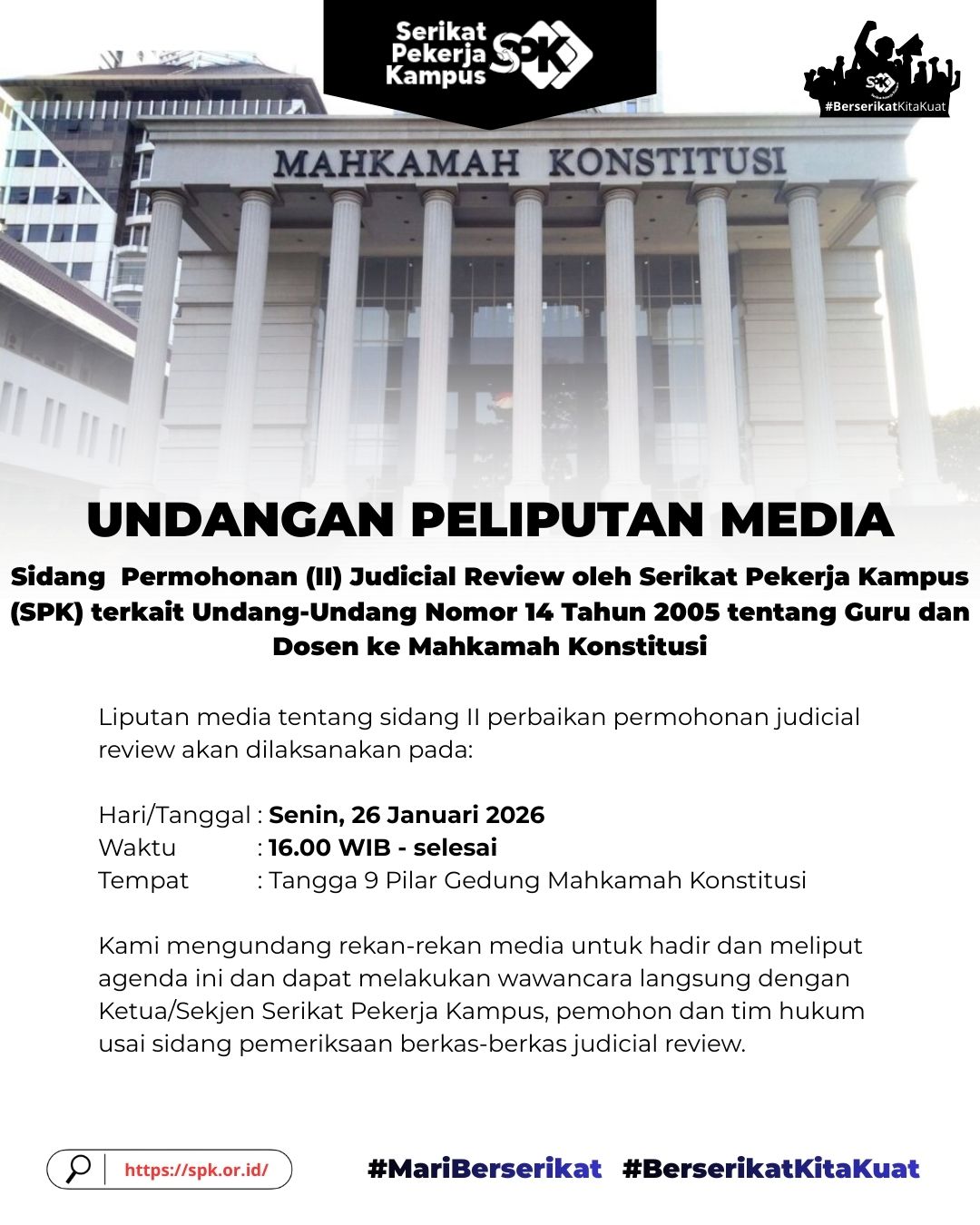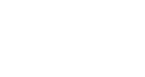Pentingnya Hak dan Perlindungan bagi Tenaga Kependidikan
Ketika masyarakat umum berbicara tentang pendidikan tinggi, hampir selalu sorotan diarahkan pada para dosen, peneliti, dan mahasiswa. Sosok-sosok ini menjadi representasi utama dunia kampus dalam benak publik—mewakili intelektualitas, riset, dan transformasi sosial. Namun, dalam keheningan dan ketersembunyian ruang-ruang administrasi, laboratorium, ruang kebersihan, dan keamanan, terdapat pilar-pilar penting lainnya yang menopang keberlangsungan sistem pendidikan tinggi: Tenaga Kependidikan.
Tenaga Kependidikan (Tendik)—sering kali disebut dengan istilah “staf non-akademik”—juga merupakan salah satu penggerak dalam sistem pendidikan tinggi. Mereka tidak berdiri di podium memberi kuliah, tetapi kehadiran mereka menjadi krusial untuk memastikan kampus tetap berjalan. Dari pengelola administrasi akademik, pustakawan, teknisi laboratorium, hingga petugas kebersihan dan keamanan, seluruh elemen tersebut berkontribusi pada terciptanya ekosistem pendidikan yang fungsional dan manusiawi.
Namun, di balik pentingnya peran mereka, hak-hak dan perlindungan bagi Tenaga Kependidikan masih menjadi ruang gelap yang kerap luput dari perhatian. Padahal, menurut kerangka hukum nasional dan norma konstitusional, posisi mereka sebagai pekerja kampus mestinya dijamin dan dihargai sebagaimana layaknya profesi lain dalam ekosistem pendidikan.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 39 ayat (1) menegaskan bahwa Tenaga Kependidikan memiliki tanggung jawab dalam administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan. Ini bukanlah peran tambahan atau pelengkap. Ini adalah bagian integral dari fungsi lembaga pendidikan.
Dalam arsitektur sistem pendidikan nasional, posisi tenaga kependidikan (Tendik) sejatinya tidak berada di pinggiran. Mereka bukan figuran dalam panggung besar perguruan tinggi, melainkan fondasi operasional dan teknis yang menopang keberlangsungan pendidikan. Pernyataan ini bukan sekadar retorika. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara eksplisit mencantumkan posisi mereka dalam Pasal 39 ayat (1): "Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan." Kalimat ini menegaskan bahwa tugas dan fungsi Tendik tidak bersifat suplementer terhadap tenaga pendidik (dosen), melainkan komplementer dan esensial.
Lebih lanjut, Permendikbud No. 10 Tahun 2017 memperjelas cakupan profesi yang termasuk dalam kategori tenaga kependidikan. Mereka mencakup pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, psikolog, pekerja sosial, hingga tenaga kebersihan dan keamanan. Dengan kata lain, Tendik hadir dalam berbagai bentuk dan fungsi: dari yang berurusan langsung dengan pengelolaan laboratorium dan sumber belajar, hingga yang menjaga keamanan dan ketertiban fisik lingkungan kampus.
Namun demikian, pengakuan yuridis tersebut belum selalu sejajar dengan perlindungan normatif dan implementatif di lingkungan perguruan tinggi. Banyak Tendik, terutama yang berstatus kontrak atau outsourcing, masih berada dalam posisi rentan. Mereka menghadapi tantangan seperti upah di bawah standar kelayakan, absennya jaminan sosial secara menyeluruh, tidak adanya jalur pengembangan karier yang terstruktur, serta perlindungan hukum yang lemah ketika menghadapi ketidakadilan atau konflik kerja.
Padahal, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang yang sama dengan tegas menyatakan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh:
- a. penghasilan serta jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
- b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
- d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; serta
- e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
Jika hak-hak tersebut disandingkan dengan kenyataan di lapangan, terlihat ada ketimpangan antara regulasi dan realitas. Misalnya, dalam hal penghasilan yang pantas dan memadai, banyak tenaga kependidikan kontrak di perguruan tinggi negeri maupun swasta hanya menerima upah minimum regional (UMR), atau bahkan banyak di bawahnya apalagi jika dikontrakkan melalui pihak ketiga. Hal ini jelas bertentangan dengan semangat Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Lebih jauh, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan prinsip dasar perlindungan bagi semua pekerja—termasuk tenaga kependidikan—yang meliputi hak atas upah layak, jaminan sosial ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta hubungan industrial yang adil. Dalam konteks kampus, semua pekerja, baik dosen maupun Tendik, memiliki hak atas lingkungan kerja yang aman, stabil, dan memberi ruang pertumbuhan profesional.
Surat Edaran Mendikbudristek No. 8 Tahun 2021 juga menggarisbawahi kewajiban penyelenggara pendidikan tinggi untuk mengikutsertakan seluruh pekerjanya ke dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan, tanpa terkecuali status kepegawaian mereka (tetap, kontrak, atau outsourcing). Namun, data lapangan dan pengaduan yang masuk ke serikat pekerja kampus menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap ketentuan ini masih rendah, terutama di perguruan tinggi swasta yang mengalami tekanan finansial.
Namun, di balik pentingnya peran mereka, hak-hak dan perlindungan bagi Tenaga Kependidikan masih menjadi ruang gelap yang kerap luput dari perhatian. Padahal, menurut kerangka hukum nasional dan norma konstitusional, posisi mereka sebagai pekerja kampus mestinya dijamin dan dihargai sebagaimana layaknya profesi lain dalam ekosistem pendidikan.
Perlindungan Bagi Tenaga Kependidikan
Perlindungan terhadap profesi tenaga kependidikan (Tendik) di lingkungan perguruan tinggi semestinya bukan semata-mata wacana normatif, melainkan sebuah mandat etik dan yuridis yang tidak dapat dinegosiasikan. Kebutuhan akan perlindungan ini bersumber dari hak dasar manusia untuk bekerja secara bermartabat dan bebas dari perlakuan semena-mena. Hal ini selaras dengan prinsip-prinsip dalam Universal Declaration of Human Rights (1948), terutama Pasal 23 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “setiap orang berhak atas pekerjaan, atas pilihan pekerjaan secara bebas, atas kondisi kerja yang adil dan menguntungkan serta atas perlindungan dari pengangguran.”
Di level nasional, regulasi yang mengafirmasi prinsip tersebut tercantum dalam Permendikbud No. 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Dalam peraturan ini, ditegaskan bahwa bentuk perlindungan terhadap pendidik juga tenaga kependidikan meliputi:
- Perlindungan Hukum – termasuk dalam menghadapi kekerasan, intimidasi, ancaman, perlakuan diskriminatif, dan tindakan tidak adil lainnya dalam melaksanakan tugas.
- Perlindungan Profesi – mencakup hak untuk diperlakukan secara adil dalam hal ketenagakerjaan, penghargaan terhadap kompetensi, dan pengembangan profesional.
- Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja – mengatur tanggung jawab institusi dalam menyediakan lingkungan kerja yang aman dan layak.
- Perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual – bagi tenaga kependidikan yang menciptakan inovasi, perangkat kerja, atau produk intelektual lainnya dalam menjalankan tugasnya.
Dalam hal perlindungan profesi secara spesifik, Permendikbud ini menguraikan lima elemen fundamental:
- Larangan pemutusan hubungan kerja secara sepihak atau sewenang-wenang. Praktik pemutusan kontrak kerja tanpa alasan yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya melanggar hukum ketenagakerjaan, tetapi juga melemahkan rasa aman psikologis para pekerja kampus.
- Kewajiban pemberian imbalan yang wajar. Ini tidak terbatas pada jumlah nominal gaji, tetapi juga menyangkut struktur penggajian yang adil, transparansi dalam pemotongan atau insentif, serta akses terhadap tunjangan dan fasilitas sosial dasar.
- Kebebasan menyampaikan pendapat secara konstruktif. Tenaga kependidikan, sebagai bagian dari komunitas akademik, memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, termasuk menyampaikan kritik atau aspirasi terkait kondisi kerja, manajemen institusi, atau kebijakan yang memengaruhi peran mereka.
- Larangan terhadap pelecehan profesi. Ini mencakup tindakan merendahkan posisi, meremehkan kompetensi, atau mengucilkan peran tenaga kependidikan dalam forum akademik maupun administratif. Pelecehan semacam ini seringkali bersifat simbolik—terjadi dalam bentuk pengabaian, stereotipe, atau pengurangan makna kontribusi mereka dalam ekosistem pendidikan tinggi.
- Penghapusan hambatan struktural dalam pelaksanaan tugas. Banyak tenaga kependidikan menghadapi hambatan institusional seperti birokrasi yang tidak ramah, sistem pelaporan yang hierarkis dan tidak transparan, serta akses yang terbatas terhadap pelatihan dan peningkatan kapasitas profesional.
Sayangnya, dalam praktik keseharian di banyak kampus di Indonesia, prinsip-prinsip ini belum diimplementasikan secara sistemik. Salah satu contoh krusial adalah minimnya representasi tenaga kependidikan dalam struktur pengambilan keputusan. Dalam senat akademik, dewan pengelola, atau unit-unit perumus kebijakan, suara Tendik nyaris tak terdengar. Akibatnya, kebijakan kelembagaan yang dihasilkan sering kali tidak responsif terhadap kebutuhan dan realitas yang mereka hadapi.
Ketiadaan representasi ini berdampak langsung pada terbatasnya ruang artikulasi kolektif. Misalnya, ketika hak-hak normatif seperti kenaikan gaji, kejelasan status kepegawaian, atau hak atas cuti tidak dipenuhi, Tendik kerap kali tidak memiliki saluran formal yang aman untuk menyampaikan keluhan atau melakukan negosiasi. Bahkan dalam beberapa kasus, mereka menghadapi ancaman kehilangan pekerjaan hanya karena dianggap "membangkang" atau "tidak loyal" saat menyuarakan aspirasi.
Fenomena ini diperparah oleh kerentanan status kerja, di mana sebagian besar tenaga kependidikan berstatus tidak tetap (honorer, outsourcing, atau kontrak tahunan). Status ini menempatkan mereka dalam posisi tawar yang lemah. Mereka tidak hanya sulit memperjuangkan hak kolektif, tetapi juga mudah dipecat atau digantikan kapan saja, sering tanpa penjelasan atau kompensasi yang memadai.
Ketimpangan perlakuan ini menjadi lebih nyata bila dibandingkan dengan dosen, yang meskipun menghadapi tantangan serupa, umumnya memiliki perlindungan struktural yang lebih kuat—seperti keanggotaan dalam senat akademik, akses terhadap kenaikan jabatan fungsional, hingga keterlibatan dalam forum-forum strategis lembaga. Tendik, sebaliknya, kerap kali terjebak dalam posisi invisible labor—mereka bekerja secara esensial, namun keberadaannya tidak mendapat tempat yang setara dalam wacana institusional.
Dari sisi sosial-psikologis, ketidaksetaraan ini berisiko merusak motivasi kerja, menimbulkan alienasi, dan bahkan menimbulkan distrust horizontal antara pekerja kampus. Dalam jangka panjang, ini menggerus kohesi lembaga dan menghambat produktivitas kolektif. Padahal dalam banyak studi organisasi, pengakuan dan perlindungan terhadap martabat kerja telah terbukti berbanding lurus dengan efisiensi, loyalitas, dan inovasi pekerja (lihat: Deci & Ryan, 2000; Sennett, 2003).
Dengan demikian, melindungi profesi dan martabat tenaga kependidikan bukan hanya soal kepatuhan terhadap regulasi, tetapi merupakan syarat mendasar untuk membangun ekosistem pendidikan tinggi yang adil, sehat, dan berkelanjutan. Ini adalah tanggung jawab kolektif—baik manajemen kampus, pembuat kebijakan, maupun komunitas akademik—untuk membongkar struktur yang tidak setara dan menciptakan tata kelola yang inklusif bagi seluruh pekerja kampus.
Sudah saatnya narasi tentang kampus dan pendidikan tinggi tidak hanya berbicara tentang riset, kurikulum, atau capaian akademik. Kita perlu menulis ulang narasi itu dengan memasukkan dimensi keadilan sosial di dalam kampus. Kualitas pendidikan tinggi tidak hanya diukur dari prestasi akademik dosen atau mahasiswa, tetapi juga dari bagaimana kampus memperlakukan pekerjanya.
Menghormati dan melindungi tenaga kependidikan adalah prasyarat menuju kampus yang inklusif, adil, dan manusiawi. Reformasi pendidikan tinggi yang sejati tidak hanya membenahi isi kurikulum atau sistem akreditasi, tetapi juga menyentuh ranah relasi kerja dan distribusi keadilan bagi semua elemen penyusun pendidikan, termasuk mereka yang bekerja dalam diam, jauh dari sorotan kamera, tetapi dekat dengan denyut jantung kampus itu sendiri.