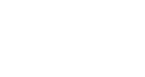KUHAP Baru: Lonceng Kematian Keadilan di Indonesia?
Jakarta – Gelombang penolakan terhadap pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru semakin menguat. Serikat Pekerja Kampus (SPK), bersama koalisi besar organisasi masyarakat sipil, menyuarakan peringatan keras bahwa regulasi baru ini berpotensi menjadi “lonceng kematian” bagi keadilan substantif dan kebebasan sipil di Indonesia.
Dalam pernyataan sikap bersama, SPK menggandeng berbagai elemen masyarakat, mulai dari Suara Ibu Indonesia, Arus Pelangi, Suara Perempuan Lingkar Napza Nusantara (SPINN), SAFEnet, hingga Sanggar Swara. Barisan ini kian menguat dengan dukungan Forum Pengada Layanan, Jala PRT, Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI), MWPRI, Manuwani Indonesia, Jakarta Feminist, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (KOMPAKS), Puspita Bahari–PPNI, Emancipate Indonesia, Koalisi Nasional Organisasi Disabilitas, serta Perhimpunan Jiwa Sehat. Mereka memandang KUHAP baru bukan sekadar pembaruan prosedural, melainkan perubahan yang akan mempengaruhi wajah penegakan hukum secara luas.
Koalisi ini menyoroti satu persoalan pokok yang dinilai mengkhawatirkan: pemberian kewenangan yang sangat besar kepada aparat penegak hukum tanpa mekanisme pengawasan yang memadai. Dalam kacamata mereka, desain kewenangan seperti ini berpotensi memperburuk praktik diskriminasi dan kriminalisasi yang selama ini telah dirasakan oleh kelompok marjinal. Komunitas LGBTIQ+, misalnya, menyuarakan ketakutan bahwa KUHAP baru membuka ruang represi yang semakin lebar, memberikan semacam “cek kosong” bagi aparat untuk bertindak sewenang-wenang. Sejalan dengan itu, para pendamping penyintas femisida dan kekerasan berbasis gender seksual mengingatkan adanya kemunduran signifikan, karena regulasi ini dinilai melemahkan penegakan hukum terhadap korporasi pelaku kekerasan seksual dan gagal mengakui femisida sebagai kejahatan khusus yang membutuhkan perlindungan ekstra.
Dari perspektif Serikat Pekerja Kampus, ancaman KUHAP baru tidak berhenti pada ranah hak sipil semata, tetapi juga menyentuh jantung kebebasan akademik dan dunia ketenagakerjaan di kampus. SPK memandang undang-undang ini telah menggeser fungsi hukum: bukan lagi sebagai instrumen untuk mengejar keadilan, tetapi cenderung menjelma menjadi alat kekuasaan yang melanggengkan budaya patriarki dan mengubah makna hukum dari ius (keadilan) menjadi sekadar legalitas formal. Dalam kerangka itu, mereka menilai kebebasan akademik terancam tereduksi. Ruang bagi akademisi untuk mengkritik atasan, elit politik, atau pemerintah dikhawatirkan semakin menyempit, terutama dalam situasi relasi kuasa yang timpang. Akademisi dipandang menjadi semakin rentan dikriminalisasi oleh aparat yang dapat bertindak sebagai “agen ganda” kepentingan kekuasaan.
Di saat yang sama, SPK menilai subjektivitas aparat penegak hukum yang tinggi berpotensi menyeret akademisi menjadi corong kepentingan tertentu melalui penafsiran hukum yang lentur dan karet. Kondisi ini, bila dibiarkan, dinilai dapat menghancurkan marwah independensi akademik di mata publik. Di ranah lain, mekanisme keadilan restoratif yang diatur dalam Pasal 79 KUHAP dikritik sebagai celah berbahaya. Pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah berpotensi diselesaikan hanya dengan “permaafan” atau kesepakatan pada tahap penyelidikan, tanpa pertanggungjawaban hukum yang jelas. Bagi koalisi ini, pola tersebut justru mengukuhkan dominasi aparat, bukan menghadirkan pemulihan yang berkeadilan.
Prinsip praduga tak bersalah juga menjadi sorotan. SPK dan jaringan organisasi sipil menilai bahwa dalam praktik yang dibayangkan oleh regulasi baru ini, seseorang yang dicurigai seolah-olah langsung ditempatkan pada posisi bersalah sejak awal proses, sehingga menjauhkan publik dari akses terhadap keadilan yang objektif. Di luar itu, mereka menegaskan bahwa ketiadaan langkah afirmatif bagi kelompok rentan—seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok miskin—membuat hukum kian terasa sebagai barang mewah. Bagi mereka yang tidak menguasai alat produksi atau sumber daya, dan tidak mampu membayar bantuan hukum yang memadai, akses terhadap keadilan akan semakin sulit, berbeda dengan elit politik atau kelompok berpunya yang lebih leluasa menggunakan jasa pengacara terbaik.
Kekhawatiran lain muncul terkait pengaturan plea bargaining dalam Pasal 1 ayat 6 yang dikhawatirkan menjadi jalur bagi pejabat atau pihak berpengaruh untuk mendapatkan keringanan hukuman atau bahkan imunitas terselubung. Potensi ini dinilai semakin diperkuat dengan keberadaan Pasal 266 yang memungkinkan terdakwa diwakili, serta pengaturan pemidanaan yang dapat disertai pemiskinan sebagaimana diatur dalam Pasal 346. Dalam pandangan SPK dan koalisi, rangkaian ketentuan ini menunjukkan bias kelas yang tajam: menguntungkan mereka yang memiliki kekuasaan dan sumber daya, sekaligus menekan mereka yang lemah secara ekonomi dan sosial. Pada akhirnya, KUHAP baru dinilai memberi legitimasi atas penyalahgunaan wewenang di bawah payung legalitas, dan mengabaikan esensi hukum sebagai pelindung warga negara.
Mencermati potensi kerusakan sistem hukum dan dampak sosial yang luas, SPK bersama koalisi organisasi masyarakat sipil memutuskan untuk mengambil sikap tegas. Mereka mendesak Presiden Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan KUHAP baru. Di saat bersamaan, koalisi ini mendorong berbagai elemen masyarakat untuk menempuh jalur konstitusional melalui pengajuan Judicial Review, baik formil maupun materiil, sebagai upaya membatalkan undang-undang yang mereka nilai cacat secara keadilan. Dalam pandangan mereka, langkah ini penting untuk memastikan bahwa reformasi hukum acara pidana di Indonesia tidak justru menjadi pintu masuk bagi erosi kebebasan sipil dan semakin jauhnya keadilan dari jangkauan rakyat.


_bergabung_dalam_Gerakan_Buruh_Bersama_Rakyat_(GEBRAK).jpeg)